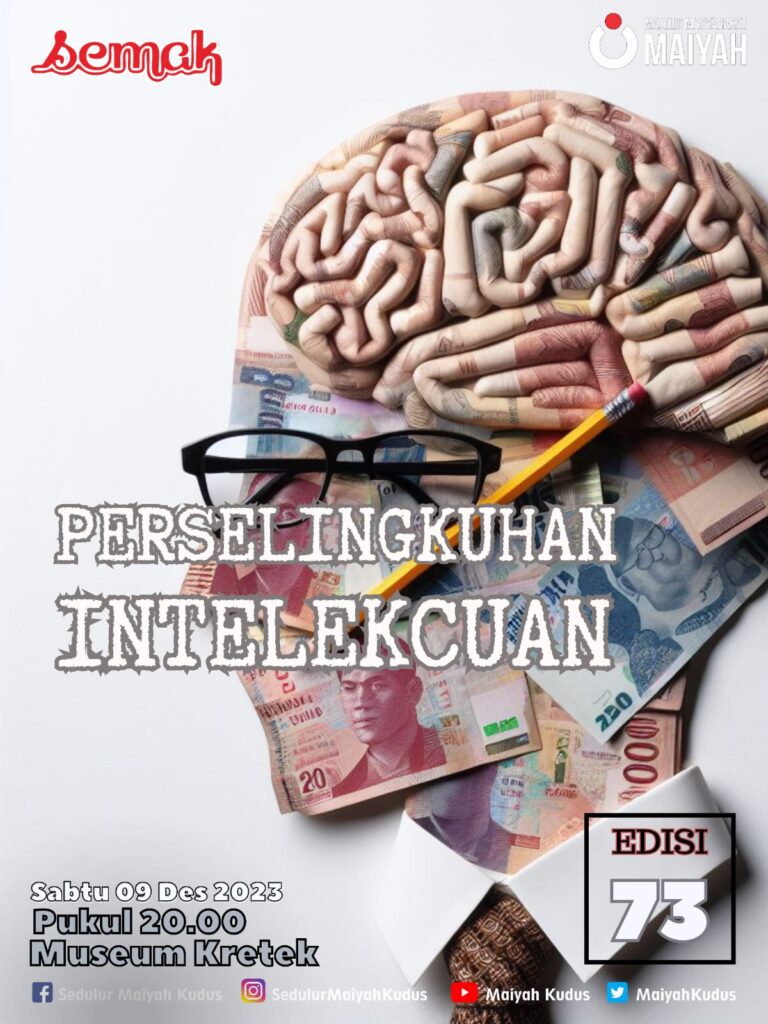Mukadimah Semak’an edisi ke-70 (09 September 2023)
Bahasa adalah penemuan terbesar umat manusia. Hal itu tampak ketika manusia menandai zaman purba, zaman sebelum kemajuan, sebagai zaman pra aksara, zaman pra bahasa, pra literasi. Melalui bahasa manusia menjadi mampu memperoleh pengetahuan dan mengaktualisasikannya. Manusia menyentuh bahasa untuk melakukan komunikasi dengan sesama, menyampaikan sebuah pesan dan menerimanya.
Sebagai suatu unsur kebudayaan, bahasa tidak hanya berhenti untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, tapi berkembang menjadi sastra: sebuah seni untuk mengatakan sesuatu yang tak terkatakan. Dalam sastra, bahasa berupaya melampaui dirinya. Keluar dari cengkeraman makna, misalnya, sebagaimana yang dilakukan Sutardji dan Afrizal Malna, atau terbebas dari sekat-sekat bidang sehingga sastra mampu melakukan interupsi pada sesuatu di luar bahasa, sebagaimana yang dilakukan Rendra, Pramoedya, dan Emha.
Keliru kalau sastra dipandang sekadar sebagai kata-kata di atas kertas. Dalam keniscayaannya, mau tak mau, sastra adalah suatu jalan kebebasan. Kebebasan dari apa, siapa, dan kemudian ke mana — ditentukan dari sistem nilai yang dianut para pelaku sastra itu. Kebebasan seperti apa yang dipandangnya. Kalau kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan atas suatu hegemoni politik, mungkin kita akan menyingkirkan para sastrawan menye-menye, atau dalam bahasa Rendra, “para penyair salon yang hanya bersajak tentang anggur dan rembulan sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya”.
Tapi, bukankakah menuntut seorang penyair untuk begini atau begitu sejatinya justru melanggar batas kebebasan? Mungkin ada saat-saat ketika kebebasan individu harus dikorbankan untuk suatu kebebasan kolektif — karena “apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan”. Rendra tak mungkin tanpa alasan mengatakannya.
Sastra yang dipandang dari perspektif kebebasan sosial itu sering disebut sebagai Sastra Pembebasan. Itu merujuk pada sastra yang melibatkan pemikiran kritis. Sebuah gerakan yang memiliki sejarah panjang. Mengilhami banyak perubahan sosial dalam masyarakat. Sebuah suara yang bersikeras mempertanyakan norma-norma sosial, politik, dan budaya yang ada, dan telah memainkan peran penting dalam proses pembebasan dan perubahan pada bangsa Indonesia.
Ada sebuah perdebatan panjang yang sampai kini mungkin belum berhenti. Sastra untuk sastra atau sastra untuk manusia. Sekilas dua hal itu mirip. Tapi, maksudnya lain: sastra untuk sastra artinya adalah sastra yang sibuk dalam dirinya. Sibuk meramu keindahan materialistik-eksistensial yang tidak masalah bila tak menciptakan perubahan sosial apa-apa: “aku nulis, puas, cukup”, misalpun harus bersentuhan, ya, cukup dengan sesama sastra, tidak perlu ke soal politik – kemanusiaan, tak perlu. Sastra yang semacam ini sebenarnya dipengaruhi oleh tradisi romantisme Eropa yang lebih dahulu mapan secara sandang-papan-pangannya. Setidaknya secara umum. Sehingga seni bagi mereka menjadi wahana untuk masturbasi saja. Yang penting enak. Meskipun tak ada yang dilahirkannya.
Kalau sastra untuk manusia agak lain. Ia adalah sastra yang merasa bertanggung jawab untuk menjadi katalisator perubahan sosial. Dipikir-pikir sebenarnya agak mumet. Para sastrawan ini bukan nabi — tapi terpanggil untuk melakukan gerakan pembebasan atas ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan, dan hegemoni — padahal kadang masih bingung untuk beli rokok dan kopi. Eh, bercyaandaa~
Ketika kita membaca sebuah karya sastra; entah cerpen, entah puisi, atau naskah drama dan darinya kita terilhami untuk lebih berkesadaran mempertanyakan status quo, kemungkinan besar itu adalah jenis sastra untuk manusia — sebuah Sastra Pembebasan, dan kita sedang dalam proses pembebasan itu. Memang ada dua perspektif dalam memandangnya: dari pembaca atau dari penulisnya. Penulis menciptakan motif. Pembaca menerima impresi. Keduanya tak harus nyambung. Kadang ada penulis yang menulis hal-hal kecil tapi pembaca menerimanya sebagai hal-hal besar. Jika satu perspektif berupaya mengirim atau menerima ilham pembebasan, maka sebuah karya layak disebut Sastra Pembebasan.
Sebuah keberuntungan sebenarnya dialami oleh para sastrawan ketika hidup dalam situasi yang tak stabil. Ketidakstabilan itulah yang melahirkan kreativitas. Entah ketidakstabilan dalam dirinya atau dalam lingkungannya. Chairil Anwar, penyair terbesar Indonesia, yang menyempurnakan bahasa Indonesia melalui puisi-puisinya — sebenarnya menderita suatu penyakit yang membuatnya harus cuci darah setiap dua minggu. Ketidakstabilan itu mendorongnya untuk mencipta puisi karena dengannya ia akan mendapat honor yang cukup untuk membayar pengobatannya. Ketika menulis puisi, Chairil Anwar juga melakukan gerakan pembebasan. Yang pertama, membebaskan dirinya dari kebutuhan untuk membayar ongkos cuci darah. Yang kedua, membebaskan masyarakat dari belenggu bahasa Melayu untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, membebaskan masyarakat dari mental yang-tertindas menuju mental yang-merdeka.
Itu satu contoh kerja-kerja pembebasan dalam sastra yang banyak mewarnai momentum penting negeri ini. Sejak kemerdekaan sampai reformasi. Sebuah sastra yang kini begitu sunyi. Bahaya bila pembebasan dirasa usang — dirasa tak dibutuhkan lagi.